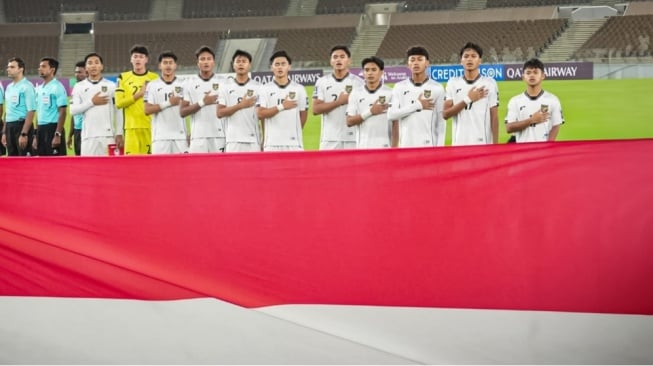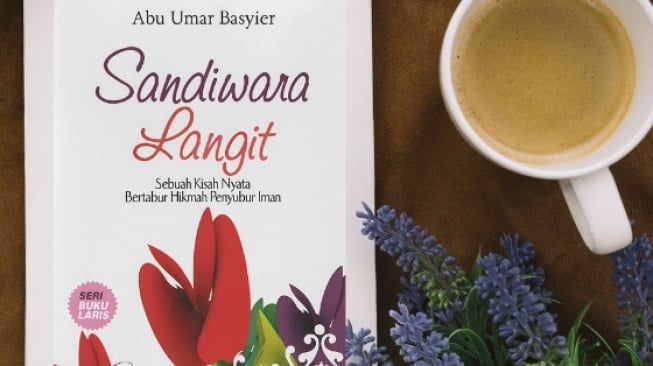News
Pesantren dan Sorotan Media: Antara Stigma dan Pemahaman

Yoursay.id - Dalam beberapa waktu terakhir, dunia pesantren kembali menjadi bahan perbincangan publik setelah sebuah tayangan di televisi nasional menampilkan narasi yang menuai kontroversi. Tayangan tersebut menggambarkan seorang kiai hidup dalam kemewahan—mengendarai mobil mewah, mengenakan sarung eksklusif—dan menuduh bahwa sumber kekayaannya berasal dari "amplop santri."
Gambarannya segera memicu gelombang protes, terutama dari kalangan pesantren, karena dianggap menyederhanakan bahkan merendahkan nilai-nilai luhur yang telah dijaga oleh lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut.
Fenomena seperti ini bukan hal baru. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, sering kali menjadi objek stigma dan kesalahpahaman. Di satu sisi, pesantren dicap konservatif, tertinggal, dan tertutup. Di sisi lain, muncul pandangan negatif yang menilai relasi antara santri dan kiai sebagai hubungan feodalistik.
Kedua persepsi itu lahir dari cara pandang luar yang kurang memahami akar budaya, spiritualitas, dan sejarah yang melatarbelakangi pesantren.
Pondasi Adab dan Ilmu
Salah satu kekeliruan terbesar dalam memahami pesantren adalah mengabaikan nilai dasar yang menjadi pondasinya. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat mempelajari ilmu agama, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas. Hubungan antara santri dan kiai bukanlah hubungan ekonomi atau transaksional, melainkan hubungan yang berlandaskan adab dan keilmuan.
Kitab Ta’limul Muta’allim karya Syekh Az-Zarnuji—yang menjadi bacaan utama hampir di seluruh pesantren—menjelaskan bahwa keberkahan ilmu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh penghormatan terhadap guru.
"Barang siapa tidak memuliakan gurunya, maka ia tidak akan memperoleh manfaat dari ilmunya," tulis Az-Zarnuji.
Dari prinsip inilah muncul berbagai tradisi yang sering disalahartikan, seperti mencium tangan guru, memberikan hadiah, atau bersikap rendah di hadapan kiai.
Sayangnya, dalam perspektif media modern yang cenderung liberal dan materialistik, tradisi-tradisi tersebut sering dianggap sebagai bentuk pengkultusan atau praktik feodal. Padahal, dalam konteks pesantren, sikap-sikap itu merupakan wujud nyata dari akhlak Islam: ta’zim (penghormatan), tawadhu’ (kerendahan hati), dan tabarruk (mencari keberkahan).
Perspektif Antropologis: Membaca Ulang Tradisi Pesantren
Antropolog seperti Clifford Geertz dan Martin van Bruinessen telah lama meneliti kehidupan pesantren dan hubungan antara kiai dan santri. Dalam The Religion of Java (1960), Geertz menggambarkan pesantren sebagai penjaga moralitas masyarakat Jawa. Ia tidak melihat hubungan kiai dan santri sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai relasi paternalistik yang didasari rasa hormat dan kasih sayang spiritual.
Sementara itu, van Bruinessen dalam karyanya Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat menegaskan bahwa penghormatan kepada kiai bukanlah feodalisme, tetapi etika sosial yang menempatkan guru sebagai penjaga ilmu dan moralitas. Ia memandang pesantren sebagai komunitas pengetahuan, tempat di mana ilmu diwariskan secara utuh—meliputi aspek intelektual, moral, dan spiritual.
Melalui cara pandang ini, pesantren dipahami sebagai entitas budaya yang khas dan kompleks. Ia tidak dapat diukur dengan standar modernisme atau kapitalisme, karena nilai-nilai yang dijunjung justru menolak logika materialisme—yakni menempatkan ilmu dan akhlak di atas harta dan popularitas.
Meluruskan Narasi dan Menghargai Warisan
Ketika media menampilkan sosok kiai yang tampak hidup mapan lalu menyimpulkan bahwa kekayaannya bersumber dari "amplop santri," itu merupakan bentuk penyederhanaan yang menyesatkan. Dalam banyak kasus, kecukupan materi seorang kiai justru dipandang sebagai berkah, bukan hasil eksploitasi.
Tradisi memberi hadiah kepada guru tidak dapat disamakan dengan praktik gratifikasi atau jual-beli jasa; ia merupakan simbol kasih sayang, penghormatan, serta harapan akan keberkahan ilmu.
Tentu, jika ada oknum kiai yang menyalahgunakan kepercayaan, kritik tetap perlu disampaikan. Namun, menggeneralisasi perilaku individu menjadi gambaran seluruh pesantren adalah bentuk ketidakadilan epistemik. Media seharusnya mampu membedakan antara penyimpangan personal dan karakter lembaga secara keseluruhan.
Penutup: Menjaga Warisan, Menolak Stigma
Selama berabad-abad, pesantren telah menjadi benteng moral, spiritual, dan intelektual umat Islam di Indonesia. Dari lingkungan inilah lahir para ulama, pemimpin, dan pejuang bangsa yang berjuang dengan keikhlasan dan integritas. Sudah semestinya kita menolak segala bentuk stigma yang merendahkan pesantren, sekaligus terus menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang dikandungnya.
Sebagai agen pembentuk opini publik, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi secara adil dan berimbang. Tidak semua hal dapat diukur dengan uang, rating, atau sensasi. Ada nilai-nilai yang hanya bisa dimengerti melalui hati yang jernih dan pemahaman yang mendalam.
Sebelum menilai tradisi pesantren dengan kacamata modern, mari kita bertanya lebih dahulu: sudahkah kita benar-benar memahami dunia mereka?