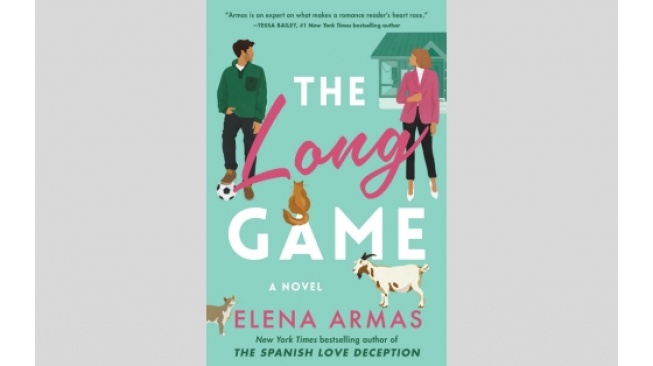kolom
Di Balik Retorika Delegasi, Wajah Lain Kemalasan Struktural

Yoursay.id - Ada satu praktik kepemimpinan yang semakin jamak kita temui di berbagai lembaga baik institusi pendidikan, birokrasi, organisasi nirlaba, hingga korporasi: delegasi tugas yang sebenarnya bukan delegasi, melainkan sekadar “menyuruh” dengan dalih pengembangan tim. Pemimpin mengklaim sedang memberdayakan, padahal yang terjadi hanyalah transfer beban tanpa orientasi pembelajaran. Ia menyebutnya pembagian tanggung jawab, padahal yang berlangsung adalah eksploitasi terselubung yang dibungkus dengan retorika kepercayaan. Dan yang lebih menyakitkan: tugas yang didelegasikan sering kali justru bisa ia kerjakan sendiri cepat, sederhana, bahkan kadang merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.
Fenomena ini memperlihatkan krisis mendasar dalam memahami makna delegasi. Delegasi bukan sekadar alih tangan pekerjaan, melainkan proses sistemik dan sadar untuk melatih, mempercayai, serta mendorong pertumbuhan kapabilitas tim. Ia mengandaikan dua prasyarat penting: bahwa tugas yang diberikan benar-benar berorientasi pengembangan, dan bahwa pemimpin sendiri telah menjalankan tanggung jawab intinya terlebih dahulu. Delegasi yang sehat lahir dari pemahaman bahwa pemimpin tidak bisa dan tidak harus melakukan semuanya, namun tetap bertanggung jawab terhadap proses dan hasil. Sebaliknya, delegasi yang salah kaprah lahir dari kemalasan terselubung, keengganan untuk turun tangan, atau dorongan ego untuk tampil sebagai pengendali, bukan pelaku.
Masalah menjadi semakin rumit ketika pemimpin yang kerap “menyuruh” justru mendapatkan segala bentuk tunjangan, insentif, dan pengakuan yang melekat pada jabatannya. Jabatan struktural bukan sekadar gelar, melainkan kontrak tanggung jawab. Ada fasilitas, keistimewaan, akses kekuasaan, dan hak istimewa yang menyertainya. Maka, ketika pemimpin hanya menjadi pemilik jabatan tanpa kesediaan menjalankan tanggung jawab praktisnya dan malah rutin melimpahkan urusan teknis pada bawahan yang tidak mendapatkan imbalan setara di sanalah terjadi ketimpangan moral dan etika. Kita menyaksikan pemisahan antara jabatan dan kerja, antara hak dan kewajiban, antara simbol dan substansi.
Tidak jarang, bawahan dipaksa memikul pekerjaan-pekerjaan remeh yang tidak menambah nilai pada pengembangan dirinya. Menyusun dokumen, mengisi absensi, memindahkan file, membuat presentasi pribadi pimpinan, hingga tugas-tugas domestik yang nyaris tak ada hubungannya dengan tugas pokok lembaga. Semua dibungkus dalam semangat loyalitas dan profesionalisme. Dan ketika bawahan menolak atau mulai bertanya-tanya, muncul tuduhan klise: “Tidak punya semangat kerja tim”, “Kurang fleksibel”, atau “Tidak punya loyalitas organisasi.”
Delegasi yang benar tidak dilandasi oleh kenyamanan pimpinan, melainkan oleh kebutuhan strategis tim. Ia bukan jalan keluar dari kemalasan, tetapi jalan masuk ke ruang pengembangan bersama. Ketika delegasi berubah menjadi alat untuk menjauhkan pemimpin dari realitas kerja, ia kehilangan legitimasi moralnya. Apalagi bila pemimpin kerap melempar kalimat: “Kamu kerjakan dulu ya, nanti saya tinggal tanda tangan.” Kalimat ini adalah potret delegasi yang sudah membusuk mengindikasikan bahwa kepemimpinan hanya sebatas stempel, bukan keterlibatan.
Lebih celakanya lagi, ada kecenderungan pemimpin semacam ini merasa sedang “memberi kesempatan” kepada orang lain untuk belajar. Ia tidak sadar, bahwa belajar bukan berarti menggantikan tugas yang menjadi hakikat jabatan orang lain. Peningkatan kapasitas SDM tidak bisa dijadikan alasan untuk melempar pekerjaan yang seharusnya berada di pundak pemimpin sendiri. Tidak semua pekerjaan bisa atau layak untuk didelegasikan. Ada tanggung jawab-tanggung jawab yang memang harus dikerjakan oleh pemegang jabatan sebagai bentuk komitmen etik dan bukti integritas.
Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa masih banyak pemimpin yang gagal membedakan antara kepemimpinan dan otoritas. Ia menyangka bahwa tugasnya hanya mengarahkan, memerintah, dan memantau. Ia menganggap jabatan sebagai hak istimewa untuk memerintah, bukan ruang untuk memikul beban kolektif bersama. Padahal, otoritas tanpa kerja nyata hanya melahirkan kekecewaan dan demoralisasi di tingkat bawah. Kepercayaan bawahan tidak lahir dari seberapa banyak pemimpin menyuruh, tetapi dari seberapa jauh ia bersedia terlibat, hadir, dan menjadi teladan kerja.
Dalam konteks yang lebih luas, praktik delegasi yang salah ini menciptakan budaya kerja yang timpang. Organisasi menjadi arena pengabdian semu di mana yang bekerja keras justru mereka yang tidak memiliki posisi formal, sementara pemegang jabatan cukup dengan instruksi. Ini bukan semangat kolaborasi, tetapi bentuk lain dari relasi kuasa yang disfungsional. Ketika praktik ini terus-menerus dipertahankan, maka pemimpin tidak hanya menciptakan tim yang lelah, tetapi juga menanamkan benih apatisme dan sinisme.
Di sisi lain, budaya kerja yang tidak memberi ruang kritik terhadap praktik kepemimpinan ini juga berkontribusi pada langgengnya delegasi yang menyimpang. Bawahan enggan mengeluh karena takut dianggap tidak kooperatif. Kritik dianggap ancaman. Laporan dianggap pembangkangan. Maka praktik suruh-suruh terus dilanggengkan dalam senyap, dibungkus oleh budaya ewuh pakewuh dan rasa tidak enak. Pemimpin merasa semua baik-baik saja, padahal kepercayaan dan semangat kerja tim sedang terkikis pelan-pelan.
Dalam organisasi yang sehat, delegasi dilakukan bukan untuk mempermudah pemimpin, melainkan untuk memperkuat sistem. Pemimpin yang berintegritas justru akan memilih untuk mengerjakan hal-hal yang memang menjadi bagian dari tugas dan kewajibannya, bahkan jika itu tampak sepele. Ia tahu bahwa jabatan bukan hanya tentang menyuruh, tapi tentang kesediaan untuk ikut menanggung. Ia sadar bahwa tim yang sehat tidak dibentuk oleh perintah sepihak, tetapi oleh kolaborasi yang saling menguatkan.
Jika pemimpin bisa menyusun laporan sendiri, mengatur jadwal sendiri, atau membuat keputusan sederhana sendiri, maka tidak ada salahnya untuk melakukannya. Justru di situlah integritas diuji. Seorang pemimpin bukan dinilai dari seberapa banyak ia menyuruh orang lain bekerja untuknya, tetapi dari seberapa siap ia bekerja untuk timnya. Delegasi seharusnya menjadi strategi pengembangan tim, bukan tameng untuk menghindari kerja teknis.
Kini saatnya kita berhenti menyamakan “menyuruh orang lain” dengan “memimpin”. Kini waktunya untuk menyadari bahwa kerja organisasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang tahu batas antara berbagi tanggung jawab dan membebani. Delegasi yang tidak disertai tanggung jawab bukan strategi manajemen, tapi bentuk pelarian. Dan pemimpin yang terus-menerus lari dari pekerjaan praktisnya dengan alasan "itu bisa dikerjakan orang lain" sedang menciptakan kehancuran perlahan yang tak kasat mata.
Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita membutuhkan pemimpin yang tahu kapan harus memimpin dari depan, kapan harus bekerja bersama, dan kapan harus mendorong orang lain tampil. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika ia terlebih dahulu punya kemauan untuk bekerja, bukan sekadar menyuruh. Kepemimpinan bukan privilege untuk memindahkan beban, melainkan kesempatan untuk menunjukkan tanggung jawab.