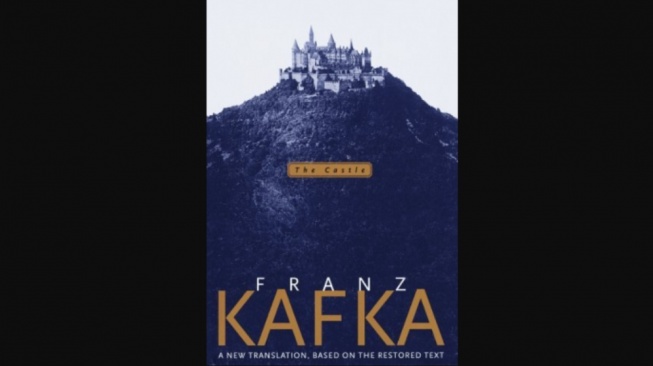kolom
BPJS Kesehatan Pangkas 21 Layanan: Efisiensi Anggaran atau Eliminasi Hak Rakyat?

Suara.com - Pagi itu di sebuah desa kecil di ujung Flores, Maria — seorang ibu muda — berjalan tertatih menyusuri jalanan tanah merah. Perutnya yang membesar menandakan usia kandungan yang hampir tujuh bulan. Ia menuju puskesmas, berharap mendapatkan tablet penambah darah seperti biasa. Tapi kali ini, petugas menyambutnya dengan senyum canggung dan kabar buruk.
“Maaf, Bu. Anemia kehamilan sudah tak ditanggung lagi oleh BPJS. Harus bayar mandiri.”
Maria tertegun. Uang yang dibawanya hanya cukup untuk ongkos ojek dan membeli beras tiga hari. Ia pulang dengan langkah lebih berat dari saat datang. Bukan karena kehamilan, tapi karena kenyataan: negara tak lagi mau menanggung sakitnya.
Cerita Maria bukan satu-satunya. Di berbagai pelosok Indonesia, kabar serupa menyebar lebih cepat dari virus. Mulai Juli 2025, sebanyak 21 jenis penyakit dan layanan kesehatan resmi dihapus dari daftar tanggungan BPJS Kesehatan. Alasan resminya? Efisiensi anggaran.
Di atas kertas, itu tampak rasional. Tapi di dunia nyata, ini adalah ironi: negara memilih sehatnya anggaran dibanding sehatnya rakyat.
Dulu Jaminan, Kini Judi Kesehatan
Dulu, saat BPJS Kesehatan pertama kali diluncurkan, suasananya seperti pesta demokrasi. Masyarakat dari berbagai latar belakang merasa setara: buruh, petani, nelayan, hingga pegawai rendahan bisa mengakses rumah sakit tanpa rasa malu.
Namun kini, rasa itu perlahan menguap. Seperti tamu yang tak lagi diundang, rakyat kecil merasa ditinggalkan.
Seorang petani tua di Klaten bercerita bahwa ia harus merelakan pengobatan gatal kronisnya karena pengobatan kulit sudah dikeluarkan dari jaminan. "Katanya cuma penyakit kulit, tapi saya tak bisa tidur, tak bisa kerja. Kalau negara tak mau tanggung, siapa lagi?" keluhnya.
Ketika 21 layanan dihapus, tak ada konsultasi. Tak ada jeda waktu untuk adaptasi. Publik seperti dipaksa menelan pil pahit tanpa air minum. Lebih parah, tak ada penjelasan transparan mengenai indikator penyakit mana yang dianggap layak dibiayai dan mana yang tidak. Rakyat pun bertanya-tanya: apakah ini efisiensi atau eliminasi?
Ketimpangan yang Kini Sah Secara Sistem
Di kota besar, orang sakit bisa memilih: klinik swasta, rumah sakit premium, atau bahkan dokter langganan yang datang ke rumah. Tapi di pelosok, akses terhadap layanan kesehatan sering kali seperti menunggu bulan jatuh: langka dan mustahil.
Laporan Anindya et al. (2020) menunjukkan bahwa wilayah 3T masih mengalami ketimpangan fasilitas dan tenaga medis yang serius. Ketika BPJS memutuskan mengurangi jaminan, maka kelompok ini bukan hanya menderita karena kurang fasilitas, tapi juga karena kehilangan jaminan.
Situasinya seperti ganda penalti bagi mereka yang sudah kalah sejak awal. Mereka miskin, mereka jauh dari kota, dan kini mereka juga kehilangan akses pengobatan. Bukankah ini pelembagaan ketidakadilan dalam bentuk paling nyata?
Barasa et al. (2021) mengingatkan, di banyak negara berkembang, asuransi kesehatan yang tidak dirancang secara pro-miskin cenderung lebih menguntungkan kelompok kaya. Di Indonesia, skema yang semula inklusif itu kini mulai terasa eksklusif. Rakyat kecil, yang dulu digandeng, kini seolah dipersilakan jalan sendiri.
Ketika Sakit Jadi Urusan Pribadi, Bukan Hak Publik
Malam hari, di sebuah rumah kontrakan sempit di Bekasi, seorang ibu menatap anaknya yang panas tinggi. Ia tahu, seharusnya anak itu dibawa ke dokter. Tapi ia juga tahu, biaya layanan dasar anak untuk pemeriksaan ringan kini tidak semua ditanggung. Ia harus memilih: beli obat warung atau bayar listrik bulan depan.
Skenario seperti ini semakin lazim. Ketika jaminan negara ditarik pelan-pelan, beban berpindah ke pundak individu. Dan individu, terutama yang miskin, tak punya banyak pilihan. Ini bukan soal malas bekerja atau tidak ingin mandiri, tapi karena hidup sudah terlalu mahal dan negara makin pelit.
Penelitian Forster et al. (2020) pernah memperingatkan bahwa kebijakan pengetatan anggaran kesehatan, seperti yang terjadi dalam program IMF, terbukti menurunkan akses layanan dan meningkatkan kematian neonatal. Kini, Indonesia seolah mengulang naskah usang yang pernah menghantui banyak negara.
Dan jangan salah, efeknya bukan hanya angka kematian atau beban ekonomi. Ada hal yang tak kalah penting: hilangnya rasa aman sosial. Jika sakit pun tak dijamin, maka rakyat mulai bertanya, “Untuk apa saya membayar negara?”
Kalau Tak Bisa Menjamin, Setidaknya Jangan Merampas
Kabar baiknya: belum terlambat. Selalu ada ruang untuk membenahi, asal kemauan politik tak hanya muncul saat kampanye. Berikut beberapa gagasan yang bisa dipertimbangkan:
Pertama, skema subsidi silang harus lebih agresif. Orang kaya bisa membayar lebih, bahkan secara otomatis lewat pajak progresif atau iuran kelas premium. Jangan biarkan mereka menikmati fasilitas kelas atas sambil tak peduli pada yang tertinggal.
Kedua, kanal layanan alternatif perlu dikembangkan. Klinik komunitas, mobile clinic, dan kolaborasi lintas sektor bisa menjangkau mereka yang selama ini tak terlihat. Tapi ini harus didukung anggaran, bukan cuma jadi proyek CSR yang glamor di permukaan.
Ketiga, puskesmas harus jadi garda depan lagi. Bukan sekadar tempat timbang bayi, tapi pusat pelayanan serius yang dilengkapi dengan SDM dan peralatan modern. Jika negara serius, maka puskesmas bisa jadi game changer.
Keempat, digitalisasi dan transparansi adalah kunci. Publik harus tahu: layanan apa yang ditanggung, kenapa layanan tertentu dihapus, dan bagaimana bisa mengakses bantuan. Tidak bisa lagi sistem BPJS seperti kotak hitam misterius.
Jika semua ini dilakukan, maka jaminan kesehatan tak akan lagi menjadi lotere sosial. Ia akan kembali ke khitahnya: sebagai hak, bukan hadiah.
Negara Tak Seharusnya Hemat di Atas Luka
Kita tak sedang bicara soal keuangan semata. Kita sedang bicara tentang nilai. Apakah hidup sehat itu hak, atau sekadar privilese?
Jika pemerintah mulai menghapus layanan karena alasan "efisiensi", lalu apa makna dari "negara hadir untuk melindungi segenap bangsa"? Apakah melindungi hanya berlaku jika biayanya murah? Apakah rasa aman warga negara bisa ditawar?
Dalam diam, banyak warga kini belajar hemat — bukan hanya hemat uang, tapi hemat percaya. Kepercayaan pada negara yang dulu begitu besar, kini mulai tergerus. Dan jika kepercayaan itu runtuh, maka negara akan kehilangan satu hal yang tak bisa dibeli oleh APBN: legitimasi moral.
Sehat adalah hak. Dan hak tak bisa dihapus hanya karena kas negara sedang menipis. Jika negara bisa membangun ibu kota baru dengan anggaran triliunan, maka seharusnya menyelamatkan nyawa ibu hamil di pelosok tak dianggap sebagai pemborosan.