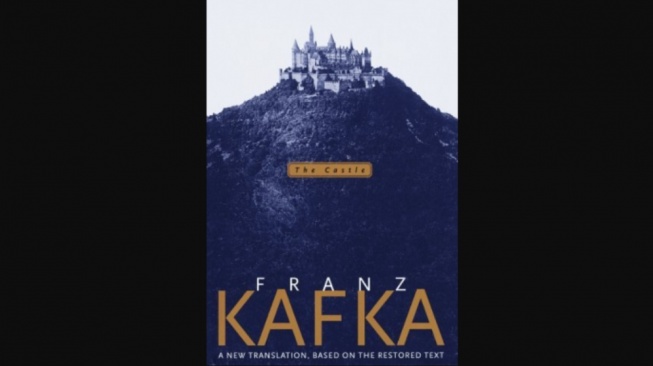kolom
RJ untuk Penghinaan Presiden: Solusi Cerdas atau Bungkam Berkedok Damai?

Suara.com - Baru-baru ini, DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat diselesaikan dengan mekanisme restorative justice (RJ), seperti tercatat dalam Draft Revisi RUU KUHAP yang sedang dibahas.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pentingnya RJ untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik. Bersamaan dengan itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa karena penghinaan Presiden adalah klacht delict (delik aduan), maka RJ sah diterapkan.
Sepintas, ide ini terdengar menjanjikan. Kita akan memasuki era dimana kritik terhadap pemimpin tidak lagi mendapat ancaman pidana. Ini tentu sebuah langkah yang bagus, mengingat betapa seringnya kita menyaksikan kasus-kasus hukum yang menjerat rakyat hanya karena celotehan atau ekspresi satir di media sosial.
Namun, apakah langkah ini benar-benar solusi efektif dalam menjaga demokrasi?
Kita tidak bisa mengelak bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden selalu menjadi sorotan dalam masalah demokrasi Indonesia. Pada 2006, Mahkamah Konstitusi sendiri pernah membatalkan pasal serupa dalam KUHP, karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan kesetaraan di mata hukum.
Presiden dan Wakil Presiden bukanlah simbol negara yang sakral layaknya bendera atau lambang negara. Keduanya adalah pejabat publik yang dipilih rakyat, digaji oleh negara, dan sudah sepatutnya menerima kritik dari publik.
Maka dari itu, menjadikan kritik yang keras atau satire sebagai tindak pidana merupakan kemunduran dalam demokrasi kita. Bahkan ketika tindakan ini dibalut dengan pendekatan restorative atau RJ, masalah utamanya tetap belum terselesaikan, yaitu mengapa kritik terhadap kekuasaan harus diberi ancaman hukum sejak awal?
Pendekatan restorative justice bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, dan mendorong penyelesaian yang lebih adil, tanpa melalui meja pengadilan.
Dalam restorative justice, pelaku dan korban akan berada dalam posisi setara. Namun dalam kasus penghinaan Presiden, perbedaan kekuasaan membuat hal itu sulit dilakukan.
Bayangkan saja, bagaimana mungkin proses penyelesaian secara damai bisa berjalan netral jika pihak yang “tersinggung” adalah kepala negara?
Jika tindak pidana penghinaan Presiden tetap dipertahankan, meskipun dengan embel-embel RJ, maka ruang kritik publik tetap dalam bayang-bayang pembungkaman. Rakyat akan lebih berhati-hati saat berbicara, bukan karena mereka tak punya dasar, tapi karena mereka takut diseret ke jeruji besi.
Di negara demokratis, kritik terhadap pejabat publik, bahkan dalam bentuk satire atau humor sekalipun, adalah bagian dari kehidupan bernegara yang tidak bisa dipisahkan. Dan pemimpin yang baik akan menerima kritik dengan lapang dada dan berusaha memperbaikinya, bukan membungkamnya.
Apalagi di zaman sekarang, media sosial membuka ruang bagi masyarakat luas untuk berekspresi. Dan apabila negara tidak bisa membedakan antara kritik dengan hinaan kebencian, maka sistem hukum yang ada justru berpotensi menjadi alat intimidasi.
Harus kita akui, langkah pemerintah untuk mencegah kriminalisasi kritik patut diacungi jempol. Ruang demokrasi memang harus terbuka seluas-luasnya.
Namun, daripada berfokus pada mekanisme "damai" setelah kritik diungkapkan, mungkin akan lebih baik jika pemerintah dan DPR merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE atau KUHP yang selama ini menjadi alat intimidasi untuk membungkam suara kritis.
Berikan definisi yang jelas tentang apa itu kritik dan apa itu penghinaan, dan tetapkan batasan yang tegas agar tidak menimbulkan beragam penafsiran.
Kesepakatan RJ untuk tindakan penghinaan Presiden dan Wapres ini adalah langkah yang perlu dicerna dengan hati-hati. Tanpa transparansi, definisi yang jelas, dan pengawasan yang ketat, dikhawatirkan ini justru menjadi alat baru untuk membungkam suara kritis.
Sebagai pejabat publik tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden seharusnya menjadi contoh dalam menerima kritik. Setajam apapun kritik, tidak seharusnya pemerintah menyiapkan jalur hukum yang membatasi suara rakyat.
Karena kritik yang keras sering kali datang dari kekecewaan yang tak kunjung didengar.