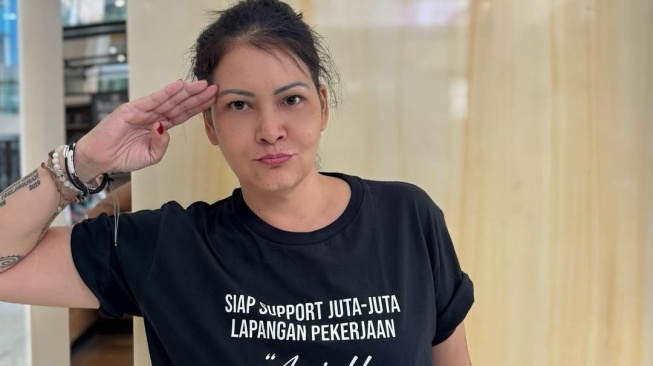News
Rumah Ibadah dan Janji Republik yang Tak Kunjung Ditepati

Yoursay.id - Indonesia dibangun di atas satu janji: keberagaman bukanlah kutukan, melainkan kekayaan. Namun, janji itu berulang kali retak ketika warga negara harus beribadah dalam rasa takut, bahkan dibubarkan.
Beberapa waktu lalu, dua kasus terjadi hampir bersamaan. Di Padang, jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) dipaksa menghentikan ibadah. Di Sukabumi, retret anak-anak Kristiani berakhir dengan perusakan rumah yang dipakai sebagai tempat berdoa. Dua peristiwa ini tidak hanya meninggalkan trauma, tetapi juga menegaskan absennya negara dalam menjamin hak konstitusional.
Pasal 29 UUD 1945 secara tegas menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan ini seharusnya final. Namun dalam praktik, regulasi di bawahnya justru mengikis perlindungan tersebut.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) menjadi contoh paling jelas. Regulasi ini mensyaratkan pembangunan rumah ibadah harus mendapatkan dukungan warga sekitar dan daftar nama jemaat dalam jumlah tertentu. Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa keyakinan seseorang harus menunggu konfirmasi tetangga?
Alih-alih sekadar tunduk pada tata ruang dan standar bangunan, rumah ibadah digantungkan pada restu mayoritas. Inilah titik rawan diskriminasi. Konstitusi menjamin, tetapi peraturan teknis justru memberi ruang penolakan berbasis sentimen.
Masalah ini menunjukkan satu wajah lain dari demokrasi Indonesia yakni paradigma mayoritas. Demokrasi dipersempit menjadi sekadar hitungan suara terbanyak, sementara perlindungan pada kelompok rentan terpinggirkan.
Ketika sebuah rumah ibadah ditolak hanya karena dianggap “mengganggu ketenteraman,” maka negara gagal menjalankan fungsi dasarnya. Sebab dalam negara hukum, rasa tidak suka tidak boleh menjadi dasar pembatasan hak. Apalagi jika ketidaksukaan itu lahir dari prasangka agama. Demokrasi seharusnya tidak berhenti pada angka. Ia mesti melindungi semua, terutama yang paling rentan.
Setiap kali kekerasan berbasis agama terjadi, pemerintah hampir selalu menggunakan narasi yang sama: menjaga kerukunan. Namun “kerukunan” yang dibangun di atas kompromi yang menekan minoritas bukanlah kerukunan, melainkan penundukan.
Sialnya, kasus-kasus seperti di Padang dan Sukabumi kerap dianggap insiden. Padahal, ia adalah simptom dari kerusakan sistemik: regulasi diskriminatif, aparat yang lamban, kepala daerah yang menghindar, serta ormas yang merasa menjadi “penjaga moralitas.”
Dalam banyak kasus, negara hadir terlalu terlambat. Aparat bergerak setelah rumah ibadah rusak, setelah ibadah dihentikan paksa, setelah trauma terlanjur terbentuk.
Pelaku intoleransi pun kerap hanya diberi teguran atau hukuman ringan. Pemerintah daerah kerap bersembunyi di balik dalih menjaga stabilitas sosial, padahal yang dilakukan adalah tunduk pada tekanan kelompok tertentu. Menteri Agama, yang seharusnya menjadi figur bagi semua agama, sering terjebak menjadi representasi mayoritas. Ketika hukum kalah oleh desakan massa, yang hancur bukan hanya hak asasi, tetapi juga akal sehat bernegara.
Pertama, regulasi diskriminatif seperti PBM 2006 harus dicabut, bukan sekadar dikaji ulang. Selama aturan itu ada, perlindungan kebebasan beribadah hanya akan menjadi janji di atas kertas. Kedua, penegakan hukum harus tegas. Mediasi tidak boleh jadi jalan pintas tanpa penghukuman. Efek jera penting untuk menunjukkan bahwa intoleransi bukan sekadar “kesalahpahaman,” melainkan pelanggaran hak asasi. Ketiga, negara harus hadir lebih awal. Aparat wajib mencegah, bukan hanya memproses. Kepala daerah harus menjadi fasilitator, bukan penonton.
Dan yang paling penting pemerintah harus menghentikan kebiasaan mendelegasikan moralitas pada kelompok sosial tertentu. Moral publik tidak bisa diserahkan pada ormas, melainkan ditegakkan lewat hukum yang inklusif dan nondiskriminatif. Rumah ibadah bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah simbol janji republik: setiap orang bebas beribadah tanpa takut.
Ketika seorang anak harus menangis karena doanya dibubarkan, itu bukan sekadar tragedi individu, melainkan kegagalan negara. Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang tersisa bukan kerukunan, melainkan ketegangan yang berulang. Dan republik ini, yang lahir dari semangat kebersamaan dalam perbedaan, akan kehilangan makna paling mendasarnya.