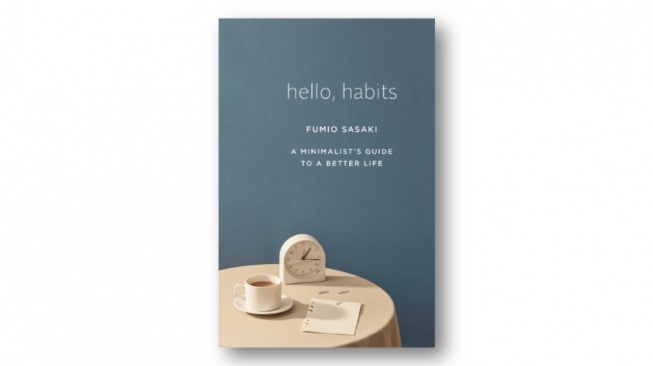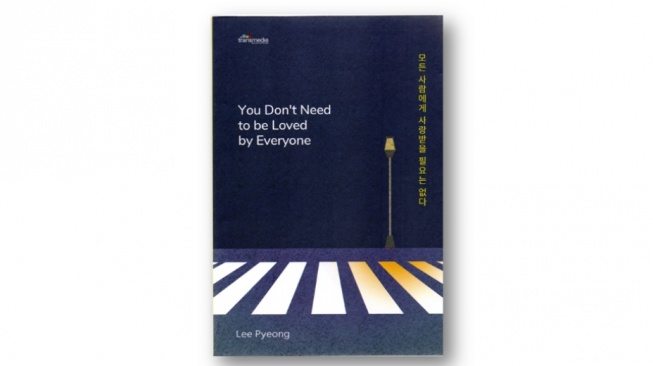kolom
Budaya Hustle Culture dan Burnout yang Disamarkan oleh Kecemasan

Suara.com - Di tengah budaya kerja yang menyanjung produktivitas tanpa henti, banyak orang merasa harus selalu sibuk agar tidak dianggap malas atau tertinggal.
Ironisnya, semakin seseorang merasa lelah secara emosional dan fisik, semakin ia terdorong untuk terus bergerak, seolah-olah diam adalah tanda kegagalan.
Fenomena ini menciptakan jebakan psikologis yaitu rasa cemas yang dibungkus dalam kesibukan. Orang terlihat produktif, namun sesungguhnya sedang mengalami burnout atau kehabisan tenaga, makna, dan motivasi, tetapi tetap memaksakan diri untuk tampak "berfungsi".
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua produktivitas yang kita banggakan benar-benar sehat, atau justru bentuk pelarian dari rasa cemas yang tak terselesaikan?
Dalam ruang diskusi yang lebih luas, penting untuk menyoroti bagaimana budaya hustle memengaruhi cara kita memandang istirahat, keberhargaan diri, dan hubungan sosial.
Saat kesibukan dijadikan alat ukur nilai pribadi, banyak yang akhirnya tidak bisa lagi membedakan antara pencapaian sejati dan sekadar bertahan dari hari ke hari.
Budaya Hustle: Prestasi atau Pelarian?
Budaya hustle atau kerja keras tanpa henti telah menjadi simbol keberhasilan, terutama di kalangan generasi muda. Ungkapan seperti “grind now, shine later” mendorong banyak orang untuk terus bekerja, bahkan saat tubuh dan pikiran sudah lelah.
Dalam narasi ini, istirahat dianggap sebagai kelemahan, dan sibuk dianggap sebagai tanda dedikasi. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang membuat orang merasa bersalah saat tidak melakukan apa-apa.
Namun, di balik semangat itu, banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang melarikan diri dari perasaan cemas, tidak aman, atau takut gagal.
Kesibukan dijadikan perisai untuk menutupi luka batin yang belum diselesaikan. Daripada menghadapi rasa tidak mampu atau ketidakpastian masa depan, orang memilih untuk terus bergerak agar tidak sempat merasa.
Burnout yang Tak Disadari
Burnout bukan lagi sekadar kondisi ekstrem, melainkan telah menjadi bagian dari rutinitas yang diromantisasi.
Banyak orang mengalami gejala seperti kelelahan kronis, kehilangan motivasi, dan sinisme terhadap pekerjaan, namun tetap menjalani hari seolah semuanya baik-baik saja.
Mereka tetap hadir, menyelesaikan tugas, bahkan terlihat produktif, padahal di dalam dirinya ada kekosongan yang makin membesar. Hal yang menyebabkan burnout sulit dikenali adalah karena sering kali ia disamarkan dengan pencapaian.
Orang-orang yang mengalami kelelahan emosional justru bisa menjadi yang paling rajin dan terlihat “sukses” di mata orang lain. Hal ini membuat intervensi menjadi terlambat karena baik diri sendiri maupun lingkungan tidak melihat ada yang salah.
Mewajarkan Diam dan Memberi Ruang
Di tengah segala dorongan untuk terus produktif, perlu ada budaya yang memulihkan yakni budaya yang mewajarkan diam, jeda, dan istirahat tanpa rasa bersalah.
Tidak semua waktu harus dimonetisasi, dan tidak semua diam adalah bentuk kemunduran. Justru dalam diam kita bisa mendengar tubuh dan pikiran kita sendiri dengan lebih jernih.
Memberi ruang untuk istirahat juga berarti memberi ruang bagi makna. Produktivitas yang sehat seharusnya tidak didorong oleh rasa takut atau kecemasan, melainkan oleh tujuan dan keseimbangan.
Mendorong refleksi, batasan kerja, dan keberanian untuk berkata “cukup” adalah langkah penting dalam melawan jebakan burnout yang terselubung dalam kesibukan.
Fenomena “cemas tapi produktif” menunjukkan bahwa tidak semua kesibukan adalah tanda kesehatan mental atau keberhasilan. Dalam banyak kasus, itu adalah bentuk pelarian dari kecemasan yang belum dihadapi.
Dalam masyarakat yang terus mendorong kita untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat, penting untuk mulai mempertanyakan untuk apa semua ini dilakukan?
Mungkin sudah saatnya kita belajar bahwa nilai diri tidak hanya ditentukan oleh seberapa sibuk kita, tetapi juga seberapa sadar kita dalam merawat diri sendiri. Sebab, produktivitas yang sehat dimulai dari ketenangan, bukan dari kepanikan yang dibungkus rapi.